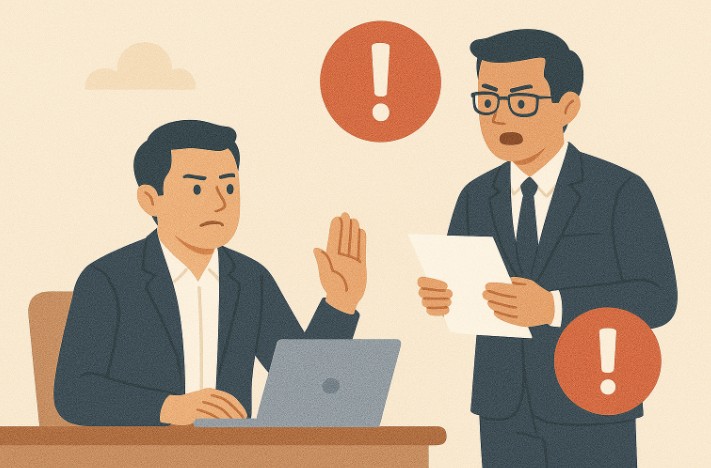Pendahuluan
Pokja (Panitia/Tim Pengadaan) memiliki peran sentral dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah: menyusun dokumen, mengelola proses tender, mengevaluasi penawaran, hingga merekomendasikan penetapan pemenang. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Pokja sering berinteraksi dengan atasan (PPK, Kepala OPD, atau pejabat lain) yang memberi arahan atau perintah. Sebagian besar arahan dapat dilaksanakan tanpa masalah, namun ada kondisi di mana perintah atasan bertentangan dengan peraturan, prinsip tata kelola, atau bahkan berisiko merugikan negara.
Mengetahui kapan Pokja bisa (dan harus) menolak perintah atasan adalah penting untuk melindungi integritas proses pengadaan, memperkecil risiko hukum, serta menjaga reputasi individu dan institusi. Penolakan bukan sekadar soal keberanian: ia harus berdasar alasan hukum, prosedural, dan etis, serta dilakukan lewat mekanisme formal yang benar. Artikel ini membahas kapan Pokja boleh menolak perintah atasan, landasan hukum dan prinsip tata kelola yang mendukung, langkah prosedural agar penolakan defensible (dapat dipertanggungjawabkan), serta potensi risiko dan cara mitigasinya. Tujuannya agar anggota Pokja tahu batas kewenangan, tahu mekanisme formal, dan mampu bertindak profesional saat menghadapi perintah yang bermasalah.
Landasan Hukum dan Prinsip Tata Kelola yang Menjadi Dasar Penolakan
Sebelum membahas kapan menolak, Pokja harus memahami kerangka hukum dan prinsip tata kelola yang menjadi dasar tindakan tersebut. Dalam pengadaan publik, keputusan dan perintah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan (misalnya Perpres/Pergub/Peraturan LK terkait PBJ), peraturan internal instansi, serta prinsip dasar pengadaan: transparansi, persaingan sehat, akuntabilitas, efisiensi, dan non-diskriminasi. Ketika perintah atasan bertentangan dengan aturan tersebut, Pokja tidak hanya berhak menolak secara substantif tetapi juga berkewajiban menolak demi kepentingan publik dan tanggung jawab fidusia.
Landasan hukum bisa berbeda di setiap institusi atau daerah, namun beberapa prinsip universal berlaku:
- Ketaatan pada hukum – perintah yang melanggar undang-undang atau peraturan pengadaan harus ditolak;
- Pemeliharaan integritas proses – perintah yang membuka peluang konflik kepentingan, kolusi, atau manipulasi dokumen harus dihindari;
- Akunabilitas keuangan – perintah yang berpotensi menyalahgunakan anggaran negara/wilayah memerlukan pengecekan dan penolakan jika tidak sesuai prosedur;
- Keselamatan dan kepatutan teknis – perintah yang mengorbankan standar mutu demi tujuan lain (mis. percepatan) harus dilawan.
Secara operasional, Pokja perlu mengetahui siapa otoritas pemberi perintah (PPK, Kepala Unit, Sekretariat) serta ruang lingkup kewenangan mereka sebagaimana tercantum dalam SK pembentukan Pokja, pedoman teknis, dan ketentuan internal. Jika perintah atasan berada di luar kewenangannya (mis. atasan memerintahkan prosedur yang hanya boleh dilakukan oleh PPK) maka Pokja sebaiknya menolak sambil meminta instruksi resmi dari pejabat yang berwenang. Bukti dokumenter (surat perintah tertulis, email, notulen) penting sebagai rujukan bila nanti muncul sengketa.
Selain hukum, prinsip etika publik menuntut bahwa penolakan disampaikan dengan cara terhormat, berdasar dan berbasis bukti. Pokja bukan “penentang otomatis” – melainkan pelaksana proses yang menjaga tata kelola. Oleh karenanya, memahami landasan hukum dan prinsip tata kelola memberi keberanian yang berbasis rasional untuk menolak perintah bila perlu.
Batasan Wewenang Atasan dan Peran Pokja: Siapa Berhak Memerintahkan Apa?
Untuk menilai apakah sebuah perintah dapat ditolak, Pokja harus tahu batasan wewenang atasan dan pembagian peran. Di struktur pengadaan umum, ada beberapa aktor utama: PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sebagai penanggung jawab anggaran dan keputusan kontraktual, Pokja sebagai pelaksana administrasi pemilihan, pengawas/konsultan, dan pimpinan OPD yang memberi arahan kebijakan. Wewenang masing-masing diatur dalam SK penunjukan, Peraturan internal, dan ketentuan perundang-undangan.
Atasan (mis. Kepala OPD) boleh memberi arahan strategis seperti menetapkan prioritas program, namun tidak selalu berwenang mengintervensi aspek teknis atau prosedural pengadaan yang menjadi domain Pokja atau PPK. Contoh batasan: hanya PPK yang berwenang menandatangani kontrak atau menetapkan penawaran pemenang; Pokja berwenang membuat rekomendasi berdasarkan evaluasi. Bila atasan memberi perintah yang memaksa Pokja mengubah hasil evaluasi tanpa dasar teknis/administratif, perintah itu berada di luar kewenangan dan dapat ditolak.
Selain itu, atasan tidak boleh memerintahkan/menekan Pokja untuk: memanipulasi kriteria penilaian; membatalkan klaim sanggah secara tidak adil; mengabaikan syarat kualifikasi; atau mengarahkan pemenang tertentu tanpa proses yang sah. Semua itu melanggar prinsip persaingan dan akuntabilitas. Di sisi lain, ada konteks di mana Pokja harus memenuhi permintaan atasan bila sesuai prosedur-mis. mempercepat proses bila ada kebutuhan darurat yang sesuai ketentuan (penunjukan langsung darurat), tetapi tetap harus melalui prosedur resmi.
Penting juga memahami istilah “perintah” vs “permintaan”. Atasan mungkin menyampaikan masukan atau dorongan untuk percepatan yang masih dalam koridor hukum; hal ini dilaksanakan dengan catatan dan dokumentasi. Perintah formal harus berbentuk surat keputusan, instruksi tertulis atau notulen rapat yang memadai. Perintah lisan yang bertentangan dengan prosedur sebaiknya tidak dituruti; sebagai gantinya minta instruksi tertulis atau rujuk pada peraturan.
Untuk mengukur kewenangan, Pokja dapat mengacu pada: SK pembentukan Pokja, pedoman teknis pengadaan, job description dalam SOP, dan kewenangan PPK. Bila kebingungan muncul, konsultasi singkat dengan unit hukum atau inspektorat internal dapat mengklarifikasi apakah perintah atasan masuk ranah legal atau administratif yang sah.
Situasi di Mana Pokja Wajib Menolak Perintah
Ada kondisi tertentu di mana penolakan bukan hanya boleh tetapi kewajiban etis dan hukum bagi Pokja. Menolak demi mencegah pelanggaran hukum, penyalahgunaan anggaran, atau membahayakan keselamatan publik menjadi tindakan yang harus diambil. Berikut situasi-situasi yang jelas memerlukan penolakan:
- Perintah yang Melanggar Peraturan Pengadaan
Misalnya memerintahkan untuk mengubah dokumen evaluasi, menurunkan standar kualifikasi, atau memaksa penetapan pemenang yang tidak memenuhi syarat. Karena peraturan pengadaan mengikat, tindakan semacam itu berpotensi menimbulkan sanggahan dan temuan audit. Pokja wajib menolak sambil menyiapkan bukti kenapa keputusan evaluasi diambil. - Perintah yang Mengarah pada Konflik Kepentingan atau Kolusi
Bila atasan menyuruh memilih penyedia tertentu tanpa prosedur kompetitif atau menunjukkan hubungan pribadi/keuangan dengan calon penyedia, Pokja wajib menolak dan melaporkan ke unit pengawasan internal. Membiarkan hal ini berlanjut berarti ikut serta dalam pelanggaran etika dan hukum. - Perintah yang Mengabaikan Keselamatan Teknis atau Standar Mutu
Contoh: perintah untuk menerima barang yang diverifikasi tidak memenuhi standar mutu demi percepatan. Pokja harus menolak karena menerima barang bermutu rendah berisiko membahayakan publik dan berdampak biaya pemeliharaan tinggi di masa depan. - Perintah untuk Memalsukan Dokumen atau Menghilangkan Bukti
Praktik pemalsuan dokumen kontrak, berita acara, atau bukti uji adalah tindak pidana administratif/korupsi. Pokja wajib menolak, mendokumentasikan permintaan tersebut, dan melaporkan bila perlu. - Perintah di Luar Kewenangan Hukum Atasan
Jika atasan memerintahkan hal yang hanya boleh dilakukan oleh otoritas lain (mis. menandatangani kontrak yang hanya menjadi kewenangan PPK), Pokja harus menolak dan meminta instruksi resmi dari pejabat yang berhak.
Dalam semua situasi di atas, penolakan disertai tindakan pendukung: mencatat perintah, meminta instruksi tertulis, melaporkan ke unit hukum/inspektorat/PPK, dan bila perlu meminta pendampingan dari atasan berwenang atau komite etika. Menolak secara defensible berarti bukan menentang atasan, tapi menjalankan amanah publik dan mencegah risiko hukum untuk instansi dan individu.
Kapan Pokja Boleh Menunda atau Meminta Klarifikasi daripada Menolak Langsung
Tidak semua perintah yang meragukan harus langsung ditolak; ada kondisi di mana menunda pelaksanaan sambil meminta klarifikasi adalah pendekatan lebih bijak. Ini berguna untuk menjaga komunikasi internal, menghindari konfrontasi, dan memberi kesempatan untuk menemukan solusi yang sesuai prosedur. Berikut ruang situasi dan tata caranya:
- Perintah yang Ambigu atau Kurang Informasi
Jika perintah tidak jelas (mis. “percepat proses” tanpa detail), Pokja sebaiknya meminta instruksi tertulis yang merinci ruang lingkup percepatan, prioritas, dan batas kewenangan. Permintaan klarifikasi dapat via email atau memo resmi sehingga ada jejak dokumenter. - Perintah yang Mengandung Risiko tetapi Dapat Dimitigasi
Misalnya atasan meminta percepatan tender. Bila percepatan memungkinkan melalui mekanisme resmi (penyederhanaan dokumen, pengurangan waktu publikasi dalam batas regulasi, atau pemakaian metode pengadaan yang sah), Pokja bisa menawarkan opsi mitigasi dan meminta persetujuan tertulis. Jika tidak memungkinkan, Pokja menjelaskan konsekuensi risiko tertulis. - Perintah Darurat yang Memerlukan Tindakan Cepat
Dalam keadaan darurat (bencana, keselamatan publik), ada mekanisme pengadaan khusus (pengadaan darurat atau penunjukan langsung) yang memungkinkan prosedur disingkat. Pokja dapat menunda kepatuhan penuh terhadap proses normal tetapi harus meminta dokumen pemicu darurat, otorisasi PPK/KPA, dan mendokumentasikan alasan darurat. - Perintah yang Memerlukan Pembahasan Lintas Unit
Jika perintah berdampak lintas unit (keuangan, teknis, hukum), lebih bijak menunda sambil memanggil rapat koordinasi singkat dengan PPK, unit hukum, dan pengguna. Hasil rapat diberi notulen dan instruksi tertulis sebelum implementasi. - Perintah yang Memerlukan Verifikasi Fakta
Misalnya atasan menerima informasi bahwa sebuah vendor berpotensi bermasalah; sebelum menindak, Pokja boleh menunda tindakan sambil verifikasi dengan unit pengawasan, mengecek database vendor, atau meminta klarifikasi resmi.
Prinsip saat meminta klarifikasi: selalu minta secara tertulis; jelaskan implikasi teknis, hukum, dan anggaran dari perintah tersebut; tawarkan alternatif yang sesuai peraturan; dan catat semua komunikasi. Menunda bukan berarti menolak: ini adalah langkah rasional yang menunjukkan upaya proaktif untuk menyeimbangkan kepatuhan prosedural dan kebutuhan instansi.
Prosedur Formal Menolak: Langkah, Dokumentasi, dan Pelaporan
Penolakan efektif harus dilakukan melalui prosedur formal agar dapat dipertanggungjawabkan. Berikut langkah terstruktur yang direkomendasikan Pokja:
- Mencatat Perintah Awal
Segera catat detil perintah: siapa pemberi, tanggal/waktu, medium (lisan/email), konteks, dan apa yang diminta. Bila perintah lisan, mintalah konfirmasi tertulis dari pemberi perintah (email atau memo) untuk kepastian bukti. - Analisis Singkat dan Konsultasi Internal
Lakukan analisis cepat apakah perintah melanggar aturan atau menimbulkan risiko. Konsultasikan dengan ketua Pokja, PPK (jika bukan atasan), dan unit hukum/inspektorat bila perlu. Dokumentasikan hasil konsultasi. - Sampaikan Keberatan Secara Tertulis
Buat surat atau memo resmi yang menyatakan keberatan Pokja dengan alasan jelas (referensi peraturan, risiko hukum, atau teknis). Surat harus sopan namun tegas, dan memuat rekomendasi alternatif bila ada. Kirimkan ke atasan pemberi perintah, dengan tembusan PPK/unit hukum/inspektorat sesuai struktur organisasi. - Minta Arahan Tertulis dari Pejabat Berwenang (Jika Perlu)
Bila konflik kewenangan, minta instruksi tertulis dari pejabat yang berwenang (mis. PPK atau Kepala OPD) yang menegaskan siapa yang berhak memerintahkan tindakan tersebut. - Catat Semua Komunikasi dan Bukti
Simpan salinan email, notulen rapat, memo, dan dokumen pendukung. Jangan menghapus atau mengubah bukti komunikasi. Jejak audit ini sangat penting bila nanti terjadi sanggahan atau investigasi. - Jika Diperintahkan Ulang Secara Tertulis Meski Bertentangan, Laporkan ke Unit Pengawas
Jika atasan tetap memerintahkan meski sudah diberi penjelasan hukum, laporkan secara resmi ke inspektorat atau unit pengawasan internal. Tindakan ini melindungi anggota Pokja dari potensi sanksi administratif/ pidana di kemudian hari. - Gunakan Mekanisme Pelaporan Perlindungan Whistleblower Bila Ada Unsur Korupsi
Bila perintah mengandung indikasi korupsi/kolusi (mis. arahan memilih vendor tertentu), gunakan mekanisme pelaporan aman (whistleblowing) yang disediakan institusi atau laporan ke aparat penegak hukum sesuai prosedur. - Jika Perlu, Minta Pendampingan Hukum
Untuk masalah besar, minta pendampingan unit hukum instansi untuk menyusun balasan resmi yang sesuai prosedur.
Penolakan yang tercatat dan disertai upaya klarifikasi menunjukkan itikad baik Pokja. Dokumen yang lengkap adalah pelindung hukum terbaik bila terjadi audit atau tuntutan di masa depan.
Risiko, Dampak Karier, dan Cara Melindungi Diri bagi Anggota Pokja
Menolak perintah atasan tidak tanpa konsekuensi personal. Anggota Pokja yang menolak dapat mengalami tekanan, risiko reputasi, atau bahkan tindakan administratif jika tidak melakukan prosedur yang tepat. Oleh karena itu penting mengetahui risiko dan cara melindungi diri.
Risiko yang mungkin muncul:
- Tekanan Organisasional: atasan mungkin memberi tekanan moral, mempersulit tugas, atau menunda keputusan administrasi terkait karier.
- Pembalasan Formal/Informal: dalam kasus ekstrim, terdapat risiko pengaduan palsu, pemindahan tugas, atau evaluasi kinerja yang tidak menguntungkan.
- Dampak Psikologis: stres dan kecemasan akibat konflik internal.
Cara melindungi diri:
- Patuhi Prosedur Formal: lakukan penolakan melalui jalur tertulis dan sesuai SOP. Dokumentasi yang lengkap mengurangi risiko tuduhan kelalaian.
- Libatkan PPK/Unit Hukum/Inspektorat: jika langkah penolakan memicu ketegangan, melibatkan pihak berwenang memberi legitimasi tindakan.
- Gunakan Tembusan (CC) pada Komunikasi: kirim salinan ke unit-unit terkait (PPK, unit hukum, atasan langsung, dan/atau sekretariat) agar semua pihak punya catatan.
- Jaga Profesionalisme dan Sikap Komunikatif: bersikap sopan dan solutif; tawarkan alternatif yang sesuai aturan. Sikap profesional memperkecil kemungkinan konflik personal.
- Ketahui Mekanisme Perlindungan Kerja: beberapa institusi punya kebijakan perlindungan pegawai yang melaporkan tindakan tak etis (whistleblower protection). Familiarisasi dengan kebijakan ini penting.
- Simpan Bukti Fisik dan Digital: arsip lengkap e-mail, memo, CV pihak eksternal, notulen rapat. Ini berguna bila diperlukan pembelaan.
- Bangun Dukungan Internal: sebelum menolak, cari dukungan dari rekan satu tim, ketua Pokja, atau pengawas. Keputusan kolektif lebih sulit dituduh sepihak.
- Pertimbangkan Konsultasi Profesional (Hukum/Serikat Pekerja): jika risiko tinggi, konsultasikan ke unit hukum atau serikat pegawai untuk nasihat perlindungan hak.
Singkatnya, menolak harus dilakukan dengan kesadaran risiko namun dilandasi hal-hal yang melindungi: dokumentasi, prosedur, dukungan institusional, dan komunikasi yang profesional. Dengan begitu anggota Pokja meminimalkan risiko personal sambil menjalankan amanah publik.
Contoh Praktis dan Contoh Surat Balasan Penolakan: Langkah Implementasi
Agar penjelasan lebih operasional, berikut contoh skenario praktis dan contoh format surat balasan penolakan yang bisa disesuaikan.
Skenario 1 – Permintaan Menurunkan Kriteria Kualifikasi
Atasan meminta Pokja menurunkan persyaratan pengalaman penyedia agar vendor tertentu bisa ikut. Tindakan: Pokja meminta penjelasan tertulis, menunjuk aturan yang relevan, dan mengirim memo resmi menolak perubahan tanpa justifikasi rasional. Jika atasan tetap memaksa, laporkan ke PPK/inspektorat.
Skenario 2 – Perintah Terima Barang Tidak Sesuai Spesifikasi
Pengawas menerima instruksi atasan untuk menandatangani berita acara penerimaan padahal uji laboratorium gagal. Tindakan: minta instruksi tertulis, catat hasil uji, buat surat penolakan penandatanganan berita acara dengan menyertakan lampiran hasil uji dan rekomendasi perbaikan.
Contoh format surat balasan penolakan (singkat dan formal):
KOP / HEADERS
Nomor: … / Tanggal: …
Kepada
Yth. [Nama Atasan / Jabatan]
di Tempat
Perihal : Tanggapan atas Instruksi Tertanggal [tanggal instruksi]
Sehubungan dengan instruksi Saudara tertanggal [tanggal] perihal [uraikan singkat perintah], bersama ini kami sampaikan bahwa Pokja Pengadaan [nama paket] tidak dapat melaksanakan instruksi tersebut karena alasan sebagai berikut:
1. Instruksi tersebut berpotensi bertentangan dengan ketentuan [sebutkan Perpres/Peraturan/Internal] khususnya Pasal/… tentang …
2. Implementasi instruksi akan menimbulkan risiko [sebutkan: hukum, anggaran, keselamatan, integritas proses] berupa …
3. Sebagai alternatif yang sesuai aturan, kami mengusulkan: [uraikan opsi: revisi dokumen melalui addendum, pemecahan paket, penjadwalan ulang, atau pengadaan darurat bila memenuhi syarat].
Demikian kami sampaikan. Untuk kejelasan lebih lanjut kami mohon arahan tertulis selanjutnya atau konfirmasi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Semua komunikasi ini kami dokumentasikan sebagai bagian dari arsip paket pengadaan.
Hormat kami,
[Nama Ketua Pokja]
Ketua Pokja Pengadaan [nama paket]
Tembusan: PPK / Unit Hukum / Inspektorat / Arsip
Catatan penggunaan: lampirkan bukti pendukung (peraturan, hasil uji, email) dan simpan salinan. Jika dibutuhkan, minta atasan menanggapi secara tertulis dalam jangka waktu tertentu (mis. 3 hari kerja). Bila tidak ada tanggapan atau tanggapan memaksa tindakan melanggar aturan, follow up ke unit pengawas.
Contoh-contoh ini membantu Pokja mengimplementasikan penolakan secara formal, profesional, dan terdokumentasi-mencegah kebingungan serta memberi jejak audit.
Kesimpulan
Menolak perintah atasan bukan tindakan yang diambil sembarangan; tetapi dalam konteks pengadaan publik, ada saat-saat ketika penolakan menjadi kewajiban untuk menjaga kepatuhan hukum, integritas proses, dan kepentingan publik. Pokja harus bertindak berdasar landasan hukum, pedoman internal, dan prinsip tata kelola yang jelas. Langkah penolakan yang defensible selalu melibatkan dokumentasi tertulis, konsultasi dengan PPK/unit hukum/inspektorat, dan upaya menawarkan alternatif yang sesuai peraturan.
Sikap profesional-komunikatif, sopan, namun tegas-membantu meredam konflik personal dan memperkuat posisi Pokja. Menunda atau meminta klarifikasi dapat menjadi solusi bila perintah masih ambigu atau dapat dimitigasi. Namun bila perintah jelas melanggar aturan atau membuka peluang korupsi, Pokja wajib menolak dan melaporkan melalui saluran resmi.
Terakhir, penolakan yang dilakukan dengan prosedur dan bukti bukan sekadar upaya pembelaan individu: ia adalah bentuk tanggung jawab publik. Dengan menerapkan langkah-langkah yang dijelaskan di atas, Pokja melindungi dirinya sendiri dan memastikan proses pengadaan tetap akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.